Deepfake: Ancaman Serius Bagi Masyarakat Indonesia
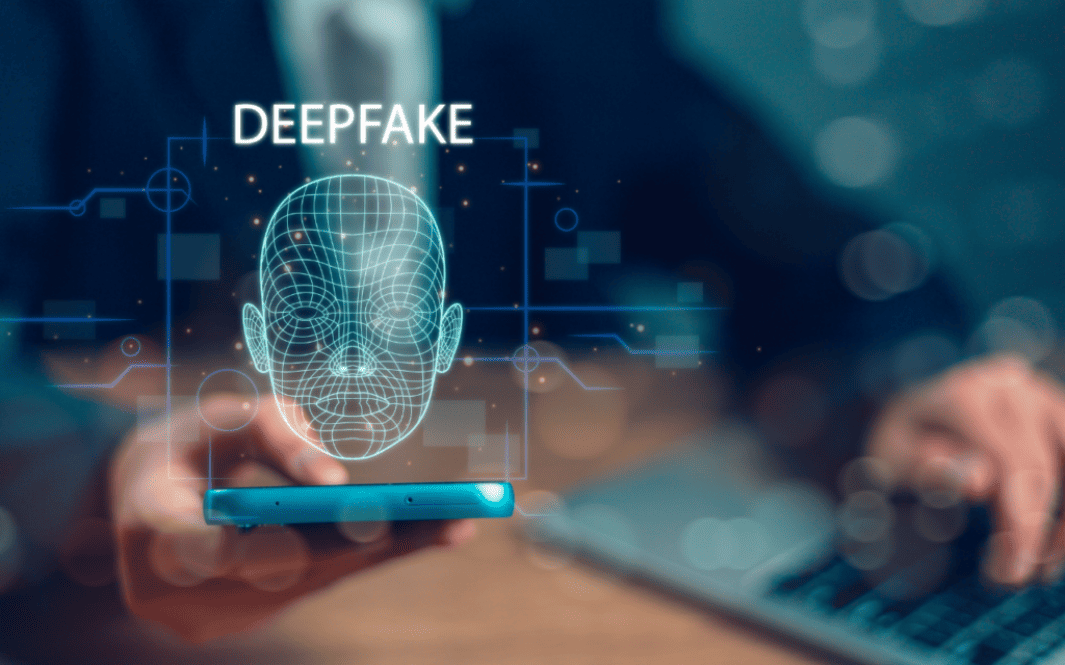
Beberapa bulan yang lalu, media sosial diramaikan dengan kasus mahasiswi ITB yang menyebarkan foto Presiden Prabowo dan mantan presiden Jokowi dalam adegan yang tidak senonoh dan terlihat begitu nyata.
Bagi orang yang melek teknologi, tentu paham bahwa foto tersebut dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan disebut sebagai deepfake. Namun, bagi mereka yang tidak, tentu bakal dianggap sungguhan dan ini bisa menjadi ancaman serius untuk masyarakat Indonesia.
Sekilas Tentang Deepfake
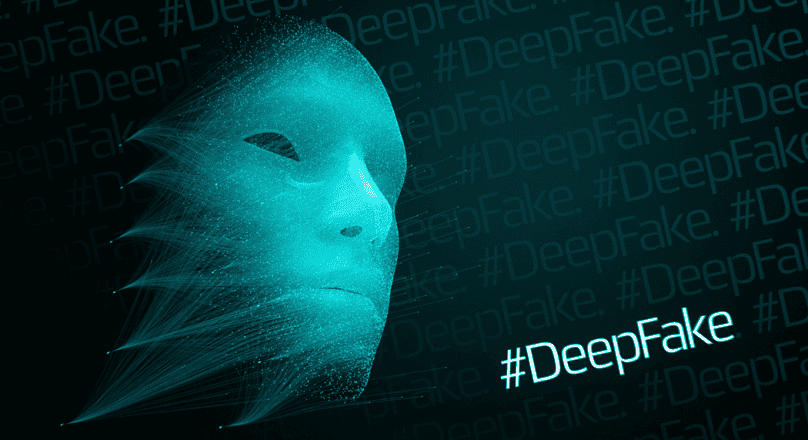
Deepfake adalah teknologi berbasis AI yang mampu menghasilkan gambar, video, atau suara palsu dengan tampilan yang sangat realistis. Teknologi ini memanfaatkan algoritma deep learning, yakni jenis pembelajaran mesin yang bekerja dengan meniru cara kerja otak manusia guna mempelajari data dalam jumlah besar dan menghasilkan konten tiruan yang nyaris sulit dibedakan dari aslinya.
Awalnya, teknologi ini dikembangkan untuk hiburan dan riset. Namun, kini, deepfake malah disalahgunakan dalam berbagai konteks, seperti perusakan reputasi, penipuan, hingga penyebaran hoaks. Melansir laman Verihubs, deepfake mampu meniru ekspresi wajah, intonasi suara, bahkan gaya berbicara seseorang dengan level presisi yang cukup tinggi.
Nah, kalau kamu pernah melihat video selebriti yang berbicara dalam bahasa yang tidak dikuasainya, besar kemungkinan itu adalah deepfake. Lantas, apa yang membuatnya berbahaya? Makin realistis sebuah konten, makin sulit pula bagi publik untuk membedakan mana yang asli dan mana yang hasil manipulasi.
Kasus Deepfake di Tanah Air
Di Indonesia, teknologi deepfake bukan sekadar ancaman biasa. Bahkan, beberapa kasus belakangan sudah berani melibatkan tokoh-tokoh penting untuk memanipulasi masyarakat secara massal.
Contohnya, kasus pada Januari kemarin, ada video manipulatif yang memperlihatkan Presiden Prabowo Subianto mengumumkan program bantuan keuangan yang langsung tersebar luas di jagat sosial. Dalam video tersebut, Presiden Prabowo terlihat dan terdengar menyampaikan bahwa setiap keluarga akan mendapatkan bantuan Rp50 juta. Padahal, pernyataan tersebut sama sekali tidak pernah dibuat oleh presiden.
Parahnya, pelaku di balik video tersebut yang berinisial AMA, sengaja membuat video yang dimaksud untuk menipu masyarakat. Ia meminta transfer biaya administrasi antara 250 ribu hingga 1 juta kepada korban. Setelah menerima uang, ia langsung menghilang.
Sebelumnya, pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo juga pernah menjadi korban. Sebuah video viral menunjukkan Jokowi fasih berbicara bahasa Mandarin. Tentu masih banyak yang terkecoh, bahkan setelah Kominfo mengonfirmasi bahwa video tersebut hasil AI. Parahnya, momen tersebut terjadi bertepatan dengan masa kampanye Pemilu 2024 sehingga sempat memengaruhi opini publik.
Deepfake di Tengah Manipulasi Informasi

Perlu dipahami bahwa masalah utama dari deepfake bukan hanya soal rekayasa gambar atau video tetapi dampak yang ditimbulkan terhadap kepercayaan publik. Gambar atau video palsu bisa digunakan untuk menyebarkan hoaks secara sistematis, khususnya dalam konteks politik dan sosial.
Menurut Appdome selaku perusahaan keamanan aplikasi global, serangan deepfake tidak mampu diatasi hanya dengan menerapkan pendekatan konvensional. Itulah sebabnya negara membutuhkan teknologi pertahanan yang adaptif dan mampu mempelajari pola baru secara langsung untuk menangkal konten-konten deepfake.
Bahkan, deepfake juga merambah ke sektor keuangan. Penjahat siber sengaja menggunakan wajah dan suara palsu untuk menipu sistem biometrik atau menyamar sebagai tokoh-tokoh penting negara atau bahkan eksekutif perusahaan. Mereka juga memanipulasi nasabah agar mau memberikan data sensitif. Parahnya lagi, data orang yang sudah meninggal dapat disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman atas nama mereka.
Meresahkannya lagi, masyarakat awam cenderung mudah percaya pada konten visual, seperti gambar dan video, dibanding teks. Hal ini membuat video deepfake sangat efektif untuk menyebarkan disinformasi yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.
Upaya Mencegah Ancaman Deepfake
Lantas, bagaimana caranya mencegah ancaman konten-konten deepfake?
Pencegahan penyebaran deepfake yang merugikan masyarakat membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri teknologi, media, dan bahkan masyarakat umum. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan:
1. Peningkatan literasi digital
Masyarakat harus bisa membekali diri dengan kemampuan berpikir kritis terhadap semua informasi yang mereka terima. Jangan mudah percaya pada video yang beredar, apalagi jika isinya terlalu mustahil atau provokatif. Cek sumber dan tanyakan pada orang yang lebih melek soal teknologi.
2. Penguatan regulasi
Pemerintah Indonesia sudah memiliki UU ITE dan revisinya yang dapat digunakan untuk menindak pelaku penyebaran konten deepfake. Sayangnya, UU ini hanya untuk menindak pelaku bukan untuk mencegah. Untuk itu, masih diperlukan regulasi tambahan yang jauh lebih spesifik terkait penggunaan dan penyebaran konten hasil manipulasi AI.
3. Kolaborasi antarsektor
Perusahaan teknologi, media, dan bahkan lembaga hukum harus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan standar keamanan digital. Pelatihan untuk para jurnalis, moderator di media sosial, dan bahkan aparat penegak hukum juga penting agar mereka siap menghadapi tantangan-tantangan di era informasi ini.
Namun, yang paling penting dari itu semua adalah edukasi publik soal bahaya deepfake. Teknologi ini boleh saja digunakan untuk hiburan yang tidak merugikan siapa pun. Akan tetapi, jika penggunaannya cenderung merugikan banyak orang, maka deepfake bisa benar-benar merugikan.
Sebagai warga digital, tentu kamu juga memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar menjadi konsumen informasi, tetapi juga penjaga kebenaran. Dengan terus meningkatkan literasi digital dan kewaspadaan, maka ancaman deepfake bisa diminimalkan. Jangan sampai kepalsuan konten merusak kepercayaan dan bahkan kehidupanmu.
